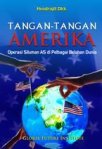©Dina Y. Sulaeman
Trend Global Pemicu Regionalisme Ekonomi
Berakhirnya Perang Dingin dan bergesernya polarisasi kekuatan dunia telah menimbulkan situasi baru dimana negara-negara menjalin kerjasama dalam ruang lingkup yang lebih terbatas dan tidak selalu menginduk kepada salah satu dari dua kekuatan dunia (AS atau Soviet) sebagaimana yang terjadi pada era Perang Dingin. Louise Fawcett (1995:22) menulis, pasca perang Dingin, negara-negara berkembang memandang bahwa pilihan kebijakan yang rasional bagi mereka adalah melakukan kerjasama regional. Melalui kerjasama regional, negara-negara berkembang bisa memperkuat jaringan (link) dengan negara maju dan pada saat yang sama, mereka bisa menampilkan sikap independensi dan swasembada yang lebih besar.
Pendapat senada juga disampaikan Andrew Wyatt-Walter, sebagaimana dikutip Fawcett (1995:25), yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong negara-negara bekerjasama membentuk regionalisme ekonomi adalah adanya perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi dunia pasca Perang Dingin. Trend global pada era pasca Perang Dingin adalah meluasnya liberalisasi perdagangan sehingga negara-negara berkembang harus berkompetisi untuk bisa masuk ke pasar negara-negara maju. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, sebagian negara merasa perlu saling bekerja sama dan membentuk regionalisme ekonomi.
Jalur Pipa Gas Iran-Pakistan-India (IPI)
Pada tahun 1993, Pakistan dan Iran telah mengumumkan rencana untuk membangun pipa gas sejauh 2775 kilometer yang menghubungkan antara ladang gas di Pars selatan (sebuah provinsi di tenggara Iran) ke kota Multan dan Karachi di Pakistan. Selanjutnya, Iran menawarkan kepada India untuk bergabung dalam proyek ini. Bila disepakati, pipa gas dari Multan akan diperpanjang hingga ke New Delhi. Pembicaraan kerjasama ketiga pihak berjalan berlarut-larut karena berbagai faktor, antara lain tidak adanya kesepakatan harga dan ketegangan politik. Bahkan, pada tahun 1999-2003, pembicaraan sempat terhenti karena ada tegangnya hubungan antara India dan Pakistan.
Namun, kebutuhan riil Pakistan dan India terhadap energi gas mendorong dilanjutkannya kembali pembahasan proyek ini. Kedua negara ini tidak punya banyak pilihan karena tingginya kebutuhan energi di dalam negeri sementara sumber daya alam mereka sangat terbatas. Tahun 2004-2005, perundingan Pakistan-India kembali dibuka. Selanjutnya, pada tahun 2008, India-Pakistan mengadakan perundingan bilateral untuk membicarakan dua proyek sekaligus, IPI dan TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) yang didukung oleh AS. Saat itu, Menteri Energi India, Murli Deora, mengatakan bahwa kedua pipa gas itu sama pentingnya bagi India. Sementara itu, Pakistan lebih memilih untuk tetap melanjutkan proyek IPI.
Pada 24 Mei 2009, Presiden Iran dan Pakistan bertemu di Teheran, menandatangani kontrak kesepakatan senilai 7,5 milyar dollar dan akan segera memulai proyek pembangunan. Bila proyek ini selesai sesuai rencana, pada tahun 2011 gas Iran sudah bisa dialirkan ke Pakistan sebanyak 8 juta kubik meter per tahun. Sebaliknya, posisi India masih maju-mundur. Tapi dalam statemen terakhirnya, menyusul penandatanganan kontrak Iran-Pakistan, Menteri Energi India kembali menegaskan komitmennya pada proposal IPI.
Aktor-Aktor yang Berperan dalam Jalur IPI
Iran
Iran adalah memiliki cadangan gas terbesar ke-2 di dunia dan produsen minyak terbesar ke-2 di dunia. Namun, Iran sendiri sangat konsumtif terhadap energi sehingga tidak tercukupi oleh minyak hasil refinery dalam negeri. Akibatnya Iran masih tetap harus mengimpor 40% minyak dari luar. Kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat membuat Iran harus terus melakukan eksplorasi migas. Artinya, Iran membutuhkan investor untuk proses eksplorasi dan pasar untuk penjualan produk migasnya.
Salah satu penyebab dari lamanya proses perundingan proyek Jalur IPI adalah terkait harga. Iran menawarkan agar harga direvisi tiap tiga atau empat tahun, namun Pakistan menginginkan agar dilakukan setiap 10 tahun. Namun, kedua pihak sepakat untuk menjadikan harga JCC (Japanese Crude Coctail) sebagai patokan. Perdebatan masalah harga ini tampaknya sudah bisa diselesaikan seiring dengan penandatanganan kontrak kerjasama antara Presiden Ahmadinejad dan PM Zardari di Teheran 24 Mei 2009.
Pakistan
Pakistan sangat berkepentingan dalam kesuksesan proyek Jalur IPI karena defisit pasokan energi dalam negeri. Gas yang disalurkan dari Iran akan mampu membangkitan 4600 megawatt listrik yang sangat dibutuhkan negara itu, jauh lebih dari cukup bagi pemenuhan kebutuhan energinya saat ini. Selain itu, Pakistan juga diperkirakan akan mendapatkan 200 juta dollar per tahun dari transit fee penyaluran gas dari Pakistan ke India.
India
Sikap India atas proyek Jalur IPI selama ini masih belum memperlihatkan kejelasan. Pada tahun 2007, India tidak lagi mengikuti pertemuan tripartit untuk membahas IPI. Padahal dalam perjanjian sebelumnya, disepakati September tahun 2009, proyek IPI akan dimulai. Bahkan India kemudian bergabung dengan ADB untuk membicarakan proyek TAPI. Pakistan juga diajak untuk bergabung dengan TAPI, namun Pakistan membutuhkan energi dalam waktu sesegera mungkin. Sementara, TAPI memiliki banyak penghalang untuk terealisasi. Lebih lagi, Pakistan melihat ada ketidakjelasan dalam volume gas dan harga yang diajukan oleh Turkmenistan (Sial, 2008).
Setelah Iran dan Pakistan menandatangani perjanjian Mei 2009, nampak gelagat China akan ikut serta dalam proyek IPI bila India memastikan tidak akan ikut. Menteri Energi India, Murli Deora segera mengeluarkan statemen, menyatakan komitmennya pada proyek IPI dan bahwa India tidak akan menunduk di hadapan tekanan pihak luar karena keperluan energi negara adalah paling utama. Tekanan pihak luar yang dimaksud Deora adalah tekanan dari AS.
China
China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia sangat memerlukan keamanan energi. China juga berkepentingan dalam suksesnya proyek IPI karena China memerlukan jalur suplai gas yang tidak berada di bawah kendali AS. Bahkan, bila India mundur dari proyek IPI, China sangat mungkin akan dilibatkan oleh Iran dan Pakistan, sehingga jalur IPI akan berubah menjadi IPC (Iran-Pakistan-China). Skenarionya, gas akan dibawa ke China dengan kereta api dari Gwadar (Pakistan).
Munculnya kemungkinan China akan ikut serta, apalagi sebelumnya, China telah ‘mengalahkan’ India dalam perebutan gas di Myanmar , membuat India terdesak dan segera menyatakan masih tetap berkomitmen pada proyek IPI. India beralasan bahwa pihak mereka belum menandatangani kontrak karena masih belum sepakat masalah harga dengan Pakistan. Kalaupun China tidak jadi ikut serta dalam proyek IPI, namun yang jelas pada bulan Maret 2009, China telah mengikat kontrak dengan Iran senilai 3,2 milyar dollar untuk melakukan eksplorasi gas di ladang minyak Pars selatan, yang hasilnya akan dialirkan ke Pakistan (dan India, bila India jadi bergabung dalam IPI).
Rusia
Rusia sangat berkepentingan dalam suksesnya proyek IPI karena akan menggagalkan proyek TAPI. Bila TAPI diimplementasikan, Rusia akan kehilangan sumber gasnya, Turkmenistan. Selama ini Rusia membeli 70% gas Turkmenistan dengan harga sangat murah untuk kemudian dijual kembali ke Ukraina, Kaukasus, dan Eropa dengan harga mahal. Selain itu, Jalur IPI akan mengalihkan gas Iran ke Asia Timur, bukan ke Eropa, sehingga Rusia tidak akan kehilangan pasarnya di Eropa. Seandainya Jalur IPI gagal, kemungkinan Iran akan menjual gasnya ke Eropa melalui Jalur Nebucco yang akan membawa gas dari wilayah Kaspia ke Eropa. Nebucco juga menjadi ancaman bagi Rusia karena akan membuat ketergantungan Eropa kepada Rusia menjadi berkurang (Chaudhary, 2000). Untuk itu, Rusia sejak awal telah menyatakan perusahaannya, Gazprom, akan ikut serta dalam proyek IPI.
Amerika Serikat
AS adalah pihak yang sangat keras berusaha menghalang-halangi proyek IPI. Bahkan, AS diberitakan telah melewati batas kesopanan dalam melarang India menjalin kontrak dengan Iran (US dropping all pretence at politeness in its efforts to dissuade India from building the pipeline). Sikap intrusif AS disebabkan karena proyek ini akan mendatangkan keuntungan finansial dan strategis bagi Iran. Selain itu, AS berusaha mempertahankan dominasinya di kawasan dengan cara menghalang-halangi Pakistan dan India dari kerjasama dengan Iran, China, dan Rusia (Sial, 2008). Sebenarnya, pada era Clinton, Jalur IPI mendapatkan dukungan dari AS karena diharapkan akan bisa mendamaikan Pakistan dan India. Namun sejak era Bush, terjadi perubahan kebijakan.
Pada tahun 2006, Duta Besar AS, Steven Mann mengatakan, “Pemerintah AS mendukung berbagai pipa dari kawasan Kaspia, tapi tetap menentang mutlak jalur pipa yang melibatkan Iran.” Sebanyak 29 pejabat AS secara kontinyu mengingatkan India dan Pakistan tentang UU AS yang akan memberi sanksi kepada perusahaan manapun yang menginvestasikan lebih dari 20 juta dollar untuk industri gas dan minyak Iran (Chaudhary, 2000).
Tahun 2007, Menteri Energi AS, Sam Bodman mengunjungi India dan mengingatkan bahwa India memerlukan AS dalam proyek nuklirnya. Namun pada saat yang sama, Bodman menjadikan proyek nuklir Iran sebagai alasan mengapa AS menentang Jalur IPI. “We believe that Iran is seeking to develop nuclear weapons and anything that will support that endeavor (such as the IPI) is something that we oppose,” kata Bodman.
Penandatanganan kontrak antara ketiga pihak (Iran-Pakistan-India) sebenarnya telah dijadwalkan akan dilakukan beberapa pekan setelah kunjungan Bodman, tetapi akhirnya batal.
Untuk membujuk India dan Pakistan, AS menawarkan proposal TAPI yang akan menyuplai gas dari Turkmenistan ke Pakistan dan India. Bila jalur TAPI berhasil dibangun, AS akan meraih dua hasil sekaligus, yaitu menghalangi Iran bekerjasama dengan Pakistan dan India, serta menghalangi Rusia mengambil keuntungan dari Turkmenistan.
Namun, proposal TAPI ternyata tidak disambut dengan baik oleh Pakistan dan India karena berbagai faktor, antara lain karena perkiraan biaya proyek yang meningkat dua kali lipat sejak tahun 2002. Selain itu, karena jalur pipa akan melewati Afghanistan, resiko yang dihadapi terlalu besar mengingat situasi negara itu masih jauh dari kestabilan. Akhirnya, Menteri Energi India menyimpulkan, “TAPI masih dalam tahap yang primitif. Kami bahkan tidak yakin apakah ada gas di sana atau tidak, dan berapa banyak gas yang ada.”
Sementara itu bagi Pakistan, Jalur IPI lebih menjanjikan karena selain bisa diimplementasikan dalam waktu dekat, juga perhitungan keuntungan yang akan didapatkannya sudah sangat jelas. Bahkan, Penasehat Perdana Menteri Pakistan. Asim Hussain menyatakan, “Penundaan pelaksanaan IPI akan menyebabkan kerugian 5 juta dollar per hari bagi Pakistan.” Saat ini Pakistan menghadapi kekurangan suplai listrik sebesar 3000 megawatt per tahunnya.
Karena itu, Pakistan tetap menandatangani kontrak dengan Iran meskipun mendapatkan tekanan dari AS. Asim Husein mengakui, “Dua negara kuat, satunya sebuah kekuatan Barat, dan satu lagi sebuah negara Islam penting, telah menekan Pakistan untuk membatalkan proyek ini.” Husein tidak menyebutkan nama dua negara yang dimaksud. Namun dia menegaskan, pemerintah Pakistan tidak akan menyerah pada tekanan asing dan akan melanjutkan proyek IPI atas dasar kepentingan nasional bersama.
Ketergantungan Ekonomi sebagai Katalis Konflik Regional
Jalur IPI memperlihatkan adanya ketergantungan antara tiga pihak, Iran, Pakistan, India. Iran sebagai negara pemilik cadangan gas terbesar kedua di dunia akan mendapatkan pasar bagi produksi gasnya, sementara Pakistan dan India mendapatkan suplai gas yang sangat mereka butuhkan dengan harga yang lebih bersaing. Ketergantungan ekonomi akan meningkatkan kebutuhan untuk melakukan kerjasama (Hurrel, 1995: 61). Dalam situasi ketergantungan yang ada, negara-negara akan menghadapi dilema koordinasi dan kolaborasi. Hal ini membuat pemerintah-pemerintahan merasa membutuhkan institusi internasional yang bisa membuat mereka mencapai kepentingan mereka melalui aksi kolektif terbatas (Keohane dalam Hurrel, 1995:61).
Di antara ketiga negara, sesungguhnya telah lama tercipta konflik dan ketegangan. Pakistan dan Iran berbatasan wilayah darat sementara India berbatasan darat dengan Pakistan. Pakistan dan Iran, meskipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim, namun berbeda mazhab. Mayoritas penduduk Iran adalah Syiah, sedangkan mayoritas penduduk Pakistan adalah Sunni. Keduanya selama ini terlibat konflik terkait ketegangan Sunni-Syiah yang dipicu oleh radikalisme kelompok Sunni di perbatasan Zahedan. Kelompok-kelompok garis keras Pakistan, antara lain Jundullah, secara sporadik melakukan pengeboman dan pembunuhan terhadap orang-orang Iran. Meskipun kelompok itu tidak mengatasnamakan pemerintah Pakistan, namun mau tak mau, hal ini menimbulkan ketegangan antara dua negara.
Sementara itu, Pakistan dan India memiliki latar belakang budaya yang jauh berbeda, karena India mayoritas berpenduduk agama Hindu sementara Pakistan mayoritas muslim. Selama sekitar 60 tahun terakhir, kedua negara selalu terlibat ketegangan politik dan bahkan pernah terjadi tiga kali perang. Salah satu penyebab utama ketegangan kedua negara adalah pertikaian masalah batas wilayah, yaitu perebutan wilayah Kashmir. Ketegangan politik ini membuat Pakistan selama ini selalu menghindari kerjasama ekonomi dengan India. Bila akhirnya kedua negara bergabung dalam Jalur IPI, hal ini akan menjadi sebuah kerjasama bersejarah.
Dari uraian singkat di atas, sekilas tampak bahwa kohesivitas di antara ketiganya sangat rapuh. Namun, menurut teori intitusionalis, kohesi regional akan muncul bukan dari terbentuknya sebuah struktur federal di antara ketiga negara tersebut, melainkan dari kerjasama-kerjasama yang terbentuk di antara negara, yang semakin lama akan membentuk jaringan yang rapat dan semakin lama akan semakin membesar (Hurrel, 1995: 64).
Louise Fawcett (1995:27) menyebutkan salah satu faktor yang mendorong terjalinnya kerjasama regional, yaitu demokratisasi. Menurutnya, demokratisasi di negara-negara telah membantu terciptanya lingkungan yang lebih ramah bagi kondisi saling ketergantungan, baik di tingkat regional maupun global. Sebagaimana diketahui, baik Iran, India, ataupun Pakistan adalah tiga negara yang menganut asas demokrasi. Meskipun memang demokrasi di Iran memiliki perbedaan, yaitu semacam “demokrasi terpimpin”, dimana ada kekuasaan yang lebih tinggi dari presiden, yang mengawasi jalannya demokrasi, yaitu Wali Faqih (ulama) .
Selain itu, lagi-lagi, faktor ekonomi akan menjadi driving force dalam peningkatan kohesivitas. Sebagaimana dikatakan Hurrel (1995:62), norma, aturan, dan institusi akan terbentuk karena ketiganya akan membantu negara-negara dalam menghadapi problem yang sama (dalam kasus IPI: problem ekonomi) dan dalam peningkatan kemakmuran.
Besarnya taruhan ekonomi yang terlibat (seperti disebutkan Asim Husaini, penundaan satu hari saja akan membawa kerugian 5 juta dollar ) sejauh ini tampaknya bisa menimbulkan keberanian Pakistan dan India untuk berkata ‘tidak’ kepada AS. Pakistan tetap menandatangani kontrak meskipun ada tekanan dari AS. Sementara itu, India meskipun belum menandatangani kontrak, tapi telah berani mengeluarkan pernyataan “tidak akan mengalah pada tekanan eksternal manapun”. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi merupakan katalis bagi konflik regional.
Dalam pandangan Chaudary (2000), terciptanya kerjasama ekonomi antara India dan Pakistan akan mendorong relasi yang yang lebih stabil di antara kedua negara yang selama ini sering berada dalam kondisi konflik. Apabila kerjasama regional antara India-Pakistan bisa terbentuk seiring dengan kolaborasi India-Iran dan Iran-Pakistan, dapat berpotensi untuk mempengaruhi antarnegara-negara di kawasan dalam isu-isu kunci, seperti terorisme Taliban, sengketa Kashmir, dan secara umum, isu-isu yang terkait dengan keamanan negara-negara di kawasan. Dampak positif proyek IPI dari sisi keamanan juga telah disadari oleh ketiga pihak, sehingga mereka menamakan proyek ini “Peace Pipeline”.
***
Note: catatan kaki dan daftar pustaka sengaja tdk ditampilkan di sini.
*